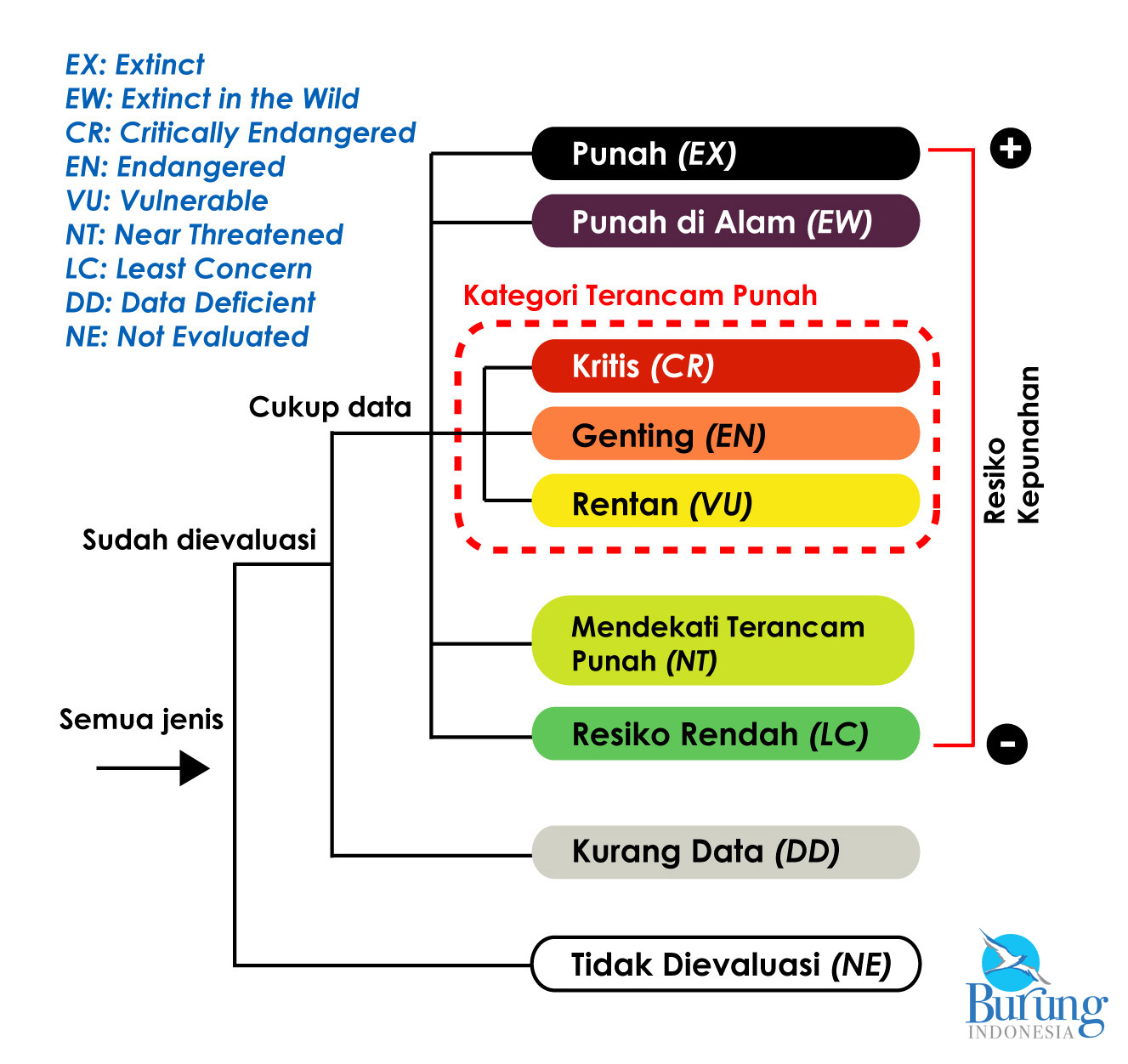Azhar Kasim, berkata lantang. Dia meminta pemerintah menindak tegas preman pengusaha sawit yang menekan kelompok pemulihan mangrove di Desa Lubuk Kertang, Langkat, Sumatera Utara.
“Preman-preman kebun sawit itu mengancam saya dengan senjata. Penegakan hukum pelaku perusakan hutan mangrove harus tegas,” katanya. Ucapan itu ditujukan kepada Hilman Nugroho, Dirjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada lokakarya pelestarian mangrove di Bali, pekan lalu.
Azhar mengatakan, ada kelompok warga mau merehabilitasi 1.200 hektar mangrove yang jadi kebun sawit. Sejak 2009, katanya, bersama Kelompok Tani Mangrove Keluarga Bahari mencoba mengembalikan mangrove dengan menjebol beberapa tembok yang dibangun perusahaan sawit.
Setelah tembok jebol, aliran air laut bisa kembali masuk dan merusak kebun sawit. Sebelumnya, perusahaan sawit mematikan mangrove di sana.
Azhar menyebut baru 275 hektar dari 1.200an hektar lahan kembali jadi hutan mangrove. “Hasil melaut berkurang karena mangrove hilang. Saya besar dari penghasilan nelayan tradisional ini,” katanya.
Nelayan tradisional di areal mangrove ini disebut ambai. Mereka biasa membuat semacam perangkap, ketika air laut surut mendapat ikan– mayoritas udang yang banyak di ekosistem mangrove.
“Sebelum diubah jadi kebun sawit sebulan penghasilan bisa Rp2-3 juta, turun jadi Rp200.000-300.000 setelah mangrove mati,” kata Azhar.
Kelompok tani ini, merancang program ekowisata mangrove untuk menambah penghasilan nelayan setelah tanaman itu dihidupkan kembali dan berusia empat tahun.
Rehabilitasi mengutamakan akses nelayan lokal ini juga dilakukan Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Dia hadir di antara kelompok warga pelestari mangrove di Indonesia.
Menurut dia, tak mudah melawan praktik pemberian izin alih fungsi mangrove. Pada 1980, kawasan timur Surabaya nyaris habis. Pernah ada yang mencoba mengembalikan hutan mangrove lalu rusak lagi. Kala jadi walikota 2010, dia mengeluarkan peraturan daerah menghentikan izin alih fungsi ini. Dari 3.600 hektar, bisa selamat 2.500 hektar menjadi ruang terbuka hijau kawasan konservasi.
“Kita akan bebaskan terus. Kawasan timur Surabaya lebih banyak terancam karena langsung berbatasan lautan lepas.”
Untuk menarik warga terlibat upaya konservasi, Risma membuat program pemberdayaan UKM lewat usaha pengolahan hasil bakau seperti tempe dan kerupuk mangrove.
Pemerintah kota juga mendorong spesialisasi tangkapan nelayan di pesisir utara. Tiap kampong punya spesifikasi hasil laut, seperti bandeng, kepiting, ikan. Risma melarang, akses air bersih dan listrik ke kawasan konservasi agar tak menarik alih fungsi lahan.
Di Bali, kondisi kebalikan. Kepala Dinas Kehutanan I Gusti Ngurah Wiranatha menyebut banyak proyek besar di kawasan hutan mangrove Ngurah Rai, misal jalan tol di perairan Teluk Benoa dan pelabuhan.
Pengelolaan hutan mangrove juga diberikan kepada investor, dan bermasalah karena dinilai sepihak dan tak trasparan dalam pemberian izin. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali 2013, menggugat Gubernur Bali ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar karena mengeluarkan surat keputusan (SK) izin pemanfaatan Taman Hutan Rakyat Ngurah Rai 122,22 hektar ke PT. Tirta Rahmat Bahari (TRB). Investor membuat hiburan dan akomodasi dalam hutan mangrove ini.
Dia mengatakan, pemerintah merencanakan revitaliasi 100 hektar pendangkalan dan diklaim tak bisa ditanami mangrove. Karena itu, harus buat alur memudahkan aliran air laut. “Belum ada reklamasi. Masih pengkajian.”
Izin reklamasi untuk PT. TWBI yang ditentang sejumlah warga antara lain, ForBali yang menganggap revitalisasi dengan cara reklamasi bukan jalan keluar. Sebab, merusak lingkungan. Pemberian izinpun dinilai tak transparan.
Tahura Ngurah Rai luas.300an hektar. Memiliki 55 jenis mangrove, dikelompokkan dalam blok perlindungan 610 hektar, pemanfaatan 350 hektar, blok lain seperti pemulihan, khusus, dan religi 413 hektar.
Hilman Nugroho membaca sambutan Menteri Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, sekitar 29% atau lebih dari 1 juta hektar hutan mangrove di Indonesia, rusak.
Dari lebih 3 juta hektar, dalam kondisi baik dan sedang sekitar dua juta. Kerusakan mangrove karena alih fungsi, tambak, pemukiman, industri, infrastruktur, pencemaran limbah, dan lain-lain.
Prof Cecep Kusmana, Guru Besar Kehutanan IPB meyakinkan mangrove meningkatkan kesuburan tanah. “Juga di pasir seperti Kepulauan Seribu. Harus dilindungi dan dikonservasi.”
Mangrove Cilacap, bisa mengurangi pencemaran dengan menyerap logam berat, intrusi air laut bisa dikurangi, di Pantai Jakarta dari satu km menjadi empat km setelah ada mangrove.
Semua bagian pohon seperti biji dan batang bermanfaat karena mengandung anti oksidan. Teknik rehabilitasi juga berkembang seperti Guludan, breakwater dan menanam di tambak.
Prof Tridoyo Kusumastanto dari IPB mengkritik kebijakan pemerintah dalam rehabilitasi mangrove. Pertama, salah menangkap isu. “Seperti kata Bu Risma, satu manusia berharga. Kalau konsep itu hilang, proses pengambilan kebijakan salah.”
Kedua, implementasi salah walau isu benar. “Implikasi luas kalau ada reklamasi, fungsi terganggu maka sulit mempertahankan keberlanjutan.”
Dwi Wahyu Daryoto, Direktur SDM dan Umum Pertamina memberikan bantuan dana sosial ke komunitas mangrove karena ingin berkontribusi ke masalah global lingkungan dan ketersediaan energi. Secara global, usaha kini harus berorientasi profit, people, dan planet.
Ratna dari Mangrove Action Project Makassar mengkritisi kebijakan pemerintah penganggaran dalam pembibitan. Anggaran, bisa hemat jika penanaman mangrove tepat. “Dari data, keberhasilan penanaman rendah. Berjuta mangrove ditanam, seringkali di tempat sama tapi gagal.” Menurut dia, acuan penanaman harus dievaluasi hingga kegagalan tak berulang.
sumber:klik disini: